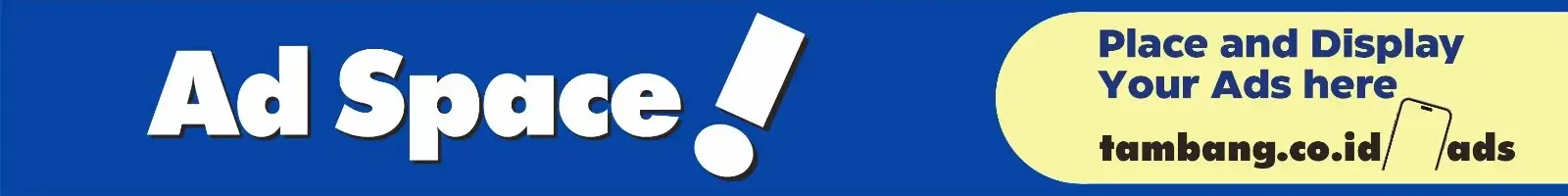Dua Wajah ESG di Industri Pertambangan dan Mineral

Rezki Syahrir, PhD *
Hari ini, Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan dan mineral tidak lagi bersifat opsional. Ia telah menjadi prasyarat—bagian dari daur hidup industri dan rantai pasok global. Akses pasar, pembiayaan, hingga legitimasi sosial semakin ditentukan oleh sejauh mana praktik bisnis dapat dibaca sebagai bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata Kelola (governance).
Namun sebelum diskursus ESG terjebak semata-mata pada isu kepatuhan, ada satu fondasi konseptual yang perlu dibedah lebih jernih: dua wajah ESG yang kerap disatukan, padahal lahir dari logika yang berbeda—ESG Standards dan ESG Guidelines. Keduanya sama-sama berbicara tentang keberlanjutan, tetapi bekerja dari arah yang berlainan dan melayani fungsi yang tidak identik.
ESG Standards pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pasar. Ia bekerja dari sisi hilir, memberi sinyal, label, dan batas etis tentang apa yang dapat diterima oleh pasar global. Standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), RMI (Responsible Minerals Initiative), atau Global Reporting Initiative (GRI) berfungsi sebagai filter eksternal—menyaring produk dan praktik yang dinilai berisiko secara etika, sosial, maupun lingkungan.
Sebaliknya, ESG Guidelines bekerja dari sisi hulu. Ia berangkat dari pertanyaan yang berbeda: bagaimana produsen dapat memproduksi secara bertanggung jawab dalam konteks operasional, sosial, dan kelembagaan yang nyata. Panduan seperti ICMM – Mining Principles & Performance Expectations, Australia’s Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry, atau Canada’s Towards Sustainable Mining (TSM) tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar global, melainkan untuk menyiapkan jalan menuju kepatuhan yang lebih kredibel dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, ESG standards protect the market, sementara ESG guidelines prepare the producers. Tantangannya bukan memilih salah satu, tetapi menempatkan keduanya secara strategis.
Ketika Industri Menyusun ESG Standards
Diskursus ini penting karena menyentuh akar legitimasi ESG dan cara pasar membaca relasi kuasa di balik sebuah “standar”. Secara prinsip, persoalannya bukan pada kapasitas teknis. Justru pelaku industri sering kali paling memahami praktik lapangan. Tantangan utamanya terletak pada legitimasi, konflik kepentingan, dan persepsi pasar.
ESG standards berfungsi sebagai alat seleksi—menentukan siapa yang “layak” dan siapa yang “tidak”. Ketika standar tersebut disusun oleh kelompok industri itu sendiri, muncul konflik kepentingan struktural: industri berperan sekaligus sebagai pembuat aturan dan subjek yang diatur. Di mata pasar, ini memunculkan pertanyaan mendasar: is this a genuine safeguard, or a self-protection mechanism?
Bagi investor institusional, OEM, dan konsumen global, ESG standards adalah alat untuk mengurangi risiko reputasi, hukum, dan etika. Karena itu, pasar cenderung lebih mempercayai standar yang disusun oleh pihak yang relatif independen dari produsen, melibatkan masyarakat sipil, serta memiliki mekanisme audit yang ketat dan transparan. Standar yang terlalu dekat dengan industri sering dipersepsikan lebih lunak, lebih berorientasi pada manajemen risiko korporasi, dan kurang kuat sebagai instrumen perlindungan publik.
Dalam konteks ini, persepsi menjadi sama pentingnya dengan substansi. Ketika industri menyusun ESG standards, pasar kerap membacanya sebagai upaya defensif—rebranding atau penahan tekanan regulasi. Jika standar tersebut longgar atau auditnya tidak benar-benar independen, risiko dicap sebagai greenwashing atau ESG-washing menjadi sangat tinggi. Dan sekali kepercayaan pasar hilang, memulihkannya hampir selalu jauh lebih sulit.
Respons pasar terhadap standar semacam ini jarang frontal, tetapi juga jarang penuh penerimaan. Investor cenderung menempatkannya sebagai informasi pelengkap, bukan dasar keputusan. Pembeli hilir tetap meminta sertifikasi independen tambahan. Sementara masyarakat sipil dan media bersikap kritis, terutama ketika terjadi pelanggaran di lapangan. Akibatnya, standar industri sering berada di posisi second-tier dalam hierarki legitimasi ESG.
Ironisnya, alih-alih menyederhanakan kepatuhan, ESG standards buatan industri justru dapat menambah kompleksitas, memicu skeptisisme, dan melemahkan posisi tawar produk di rantai pasok global.
Pola “Kegagalan Sunyi” dalam ESG
Ketika industri menyusun guidelines, pasar membaca ini sebagai:
“They are trying to improve how they work.”
Ketika industri menyusun standards, pasar sering membaca:
“They are trying to certify themselves.”
Dalam praktiknya, banyak ESG standards yang disusun atau didominasi industri tidak pernah benar-benar “gagal” secara terbuka, tetapi mengalami apa yang bisa disebut sebagai silent failure. Mereka tidak ditolak, tetapi juga tidak dipakai. Tidak menjadi rujukan investor, tidak diadopsi regulator, dan tidak dijadikan syarat pembelian oleh OEM.
Kasus World Coal Association dengan Coal Stewardship Framework sering dijadikan contoh klasik. Meski bertujuan menunjukkan praktik batu bara yang “bertanggung jawab”, kerangka ini nyaris tidak pernah dirujuk dalam diskursus ESG global. Bukan semata karena isinya keliru, melainkan karena posisi moral dan strukturalnya tidak dipercaya oleh pasar.
Contoh lain adalah Responsible Care di sektor kimia—sebuah program perbaikan internal yang sudah lama berjalan. Ia diakui sebagai upaya peningkatan praktik internal, tetapi tidak pernah menjadi basis kepercayaan publik atau investor. Sekali lagi, diterima secara teknis, namun gagal sebagai instrumen legitimasi pasar.
Pengalaman ini menjelaskan mengapa ICMM—meski beranggotakan perusahaan tambang terbesar dunia—tidak memosisikan dirinya sebagai ESG standard atau skema sertifikasi pasar. ICMM memilih jalur guidelines dan komitmen keanggotaan, dan pasar menerimanya sebagai capacity-building instrument, bukan pengganti IRMA atau RMI. Ini contoh belajar dari kegagalan sebelum kegagalan itu terjadi.
Aluminium Stewardship Initiative (ASI) menawarkan pelajaran yang lebih bernuansa. ASI bukan proyek gagal, tetapi juga bukan standar dengan legitimasi mutlak. Ia relatif diterima karena melibatkan multi-stakeholder dan fokus pada rantai pasok, bukan right to operate. Namun karena industri tetap dominan, legitimasinya bersifat kondisional dan sering dilengkapi dengan due diligence tambahan. ASI menunjukkan bahwa posisi instrumen sama pentingnya dengan isinya.
Pelajaran bagi Indonesia
Dari berbagai contoh ini, pasar global membaca satu pesan yang konsisten: ESG standards harus tampak independen dari produsen, sementara instrumen yang dekat dengan industri akan lebih kredibel bila diposisikan sebagai guidelines, frameworks, atau pathways.
Bagi Indonesia—dengan kompleksitas sosial, sensitivitas lingkungan, dan tekanan geopolitik mineral kritis—pelajaran ini krusial. ESG bukan sekadar soal memiliki instrumen sendiri, tetapi tentang memahami di ranah mana kita bermain. ESG Guidelines yang kuat dan kredibel bukanlah alternatif dari standar global, melainkan fondasi praktis yang memungkinkan industri nasional beradaptasi, patuh, dan kompetitif di berbagai rezim ESG internasional yang terus berkembang.
Dengan pemahaman posisi yang tepat, ESG dapat benar-benar menjadi instrumen leverage kualitas industri Indonesia—bukan sekadar label, tetapi jalan menuju competitive advantage industri pertambangan dalam negeri sekaligus legitimasi yang berkelanjutan di mata dunia.
*Direktur Indonesian Initiative for Sustainable Mining, Pemerhati Geopolitik, Resource Governance, dan Transisi Energi yang Berkeadilan