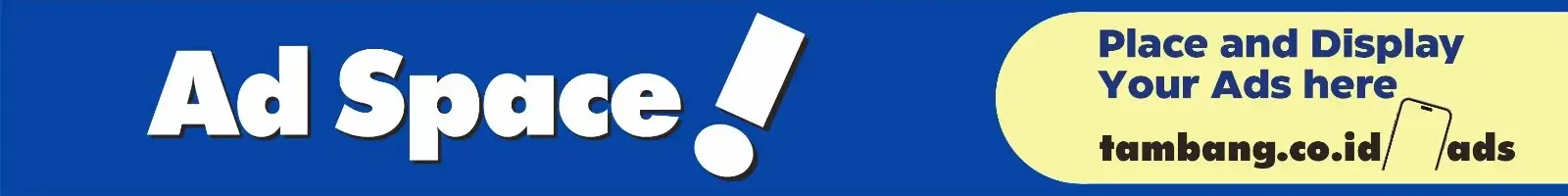(Bukan) Rezim Pemberi Izin dan Denda

Pada penghujung tahun, komunitas pertambangan mendapatkan “kado” penambah pikiran. Adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 perihal tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan yang menguat signifikan untuk berkelanjutan usaha pertambangan di Indonesia.
Dalam Keputusan yang ditetapkan dan berlaku sejak 1 Desember 2025 tersebut, diatur denda pelanggaran untuk komoditas nikel, bauksit, timah, dan juga batu bara. Besarnya maksimal mencapai Rp 6,5 miliar per hektar untuk komoditas nikel dan terendah Rp 354 juta untuk batu bara. Besaran denda itu terhitung sangat tinggi dibandingkan dengan tarif denda tunggal untuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 25 juta per hektar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dan denda di bidang kehutanan tersebut, dinyatakan bahwa tarif denda perkebunan non-sawit ditentukan oleh Menteri Keuangan dan tarif kegiatan lain ditetapkan oleh Menteri sesuai kewenangan. Ancaman denda memperhitungkan luas pelanggaran, waktu pelanggaran, dan tarif denda sebagaimana ditetapkan tersebut.
Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan tarif denda tersebut penting untuk menindak pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan. Sebagaimana diberitakan Antara (21/12/2025), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyebutkan total denda administratif yang sudah dihitung sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 29,2 triliun dari 22 perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan. Satgas telah memanggil dan memverifikasi sebanyak 120 perusahaan tambang yang tersebar di 12 provinsi. Satgas PKH sendiri dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
Isu pengenaan denda kehutanan seolah menemukan momentumnya, ketika di Sumatera bagian utara terkena bencana banjir dan longsor yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 Desember 2025 korban jiwa mencapai 1.090 orang dan pengungsi lebih dari 500 ribu. Adalah soal perusakan kawasan hutan, antara lain karena industri kelapa sawit dan pertambangan yang dituding sebagai salah satu pemicunya.
Tim Kompas (12/12/2025) mengungkap, hutan yang hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 1990-2024 rerata mencapai 36.305 hektar per tahun. Pada tahun 1990, masih terdapat 9,49 juta hektar hutan yang kemudian menyusut menjadi 8,26 juta hektar pada 2024. Penyusutan hutan 1990-2024 karena peralihan menjadi 690.777 hektar lahan sawit, kawasan tambang 2.160 hektar, kawasan perkotaan 9.666 hektar, hutan tanaman industri (HTI) 69.733 hektar.
Tidak ada yang menyanggah bahwa lingkungan adalah persoalan penting. Bahkan teramat penting karena lingkungan yang rusak tidak bisa dengan mudah dan serta merta dikembalikan ke kondisi awal. Krisis ekologi yang mengancam kehidupan manusia, pada akhirnya menuntut perubahan pola hidup dan kebijakan, termasuk praktik pertambangan secara berkelanjutan.
Pada sisi yang lain, tidak dimungkiri bahwa produk pertambangan masih signifikan untuk kemajuan peradaban dan sektor pertambangan masihlah kontributor penting perekonomian nasional. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara mencapai Rp 140,486 triliun pada tahun 2024. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan per Oktober 2025 mencapai Rp 205,7 triliun. Data pada semester I 2025, realisasi investasi sektor minerba sebesar 3,1 juta dollar AS yang meningkat dari 2,4 juta dollar AS pada periode yang sama setahun sebelumnya.
Substansi mendasar Keputusan MESDM Nomor 391/2025 karena pemerintah memandang perlunya penetapan tarif denda pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan secara jelas dan tegas. Tujuan penegakan aturan dan kepastian hukum berjalan seiring dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, Keputusan tersebut membawa konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh semua pihak.
Pertama, kelahiran Keputusan MESDM Nomor 391/2025 pada akhirnya mengharuskan setiap pelaku usaha pertambangan secara sangat (!) serius mengkaji izin penggunaan kawasan hutan yang dipegangnya, berikut seluruh kewajiban yang melingkupinya. Wilayah operasi dan batas kawasan hutan yang dipinjam-pakai harus dipertimbangkan, untuk memastikan tidak memberikan beban berlebihan, termasuk konsekuensi keuangannya. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, pemegang izin PPKH harus memenuhi 17 kewajiban, termasuk di antaranya adalah PNPB penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), reklamasi dan revegetasi, sampai pada pencegahan kebakaran dan perlindungan kawasan hutan.
Tidak bisa dimungkiri bahwa ada saja perusahaan yang secara sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak bertanggung jawab. Levelnya mulai dari pemegang izin yang lalai kewajiban, beroperasi di melebihi kawasan yang diberikan izin, atau bahkan beroperasi di kawasan hutan sekalipun belum mendapatkan izin. Untuk kasus-kasus pelanggaran yang memang disengaja, semestinya jika kemudian pemerintah menindak tegas pada kesempatan pertama.
Hal berikut yang perlu diperjelas adalah batasan andaikan pelanggaran terkait kawasan hutan dilakukan oleh pihak lain di luar perusahaan sebagai pemegang PPKH. Jika pelanggaran dilakukan secara illegal atau tanpa izin oleh pihak lain, dan kemudian perusahaan telah melaporkannya kepada penegak hukum, tentunya tidak fair jika seluruh kesalahan dibebankan kepada perusahaan pemegang PPKH.
Undang-undang Cipta Kerja juga mengatur soal “ketelanjuran”, yakni kondisi izin usaha yang telanjur berada di kawasan hutan sebelum adanya peraturan yang baru. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi pemilik usaha untuk mengajukan legalisasi dengan pemenuhan syarat administratif dalam kurun waktu tiga tahun. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagi perusahaan yang memiliki itikad baik dengan mengupayakan perizinan sesuai dengan prinsip ketelanjuran tersebut, termasuk untuk pelaku usaha pertambangan.
Harapan kepada pemerintah, pentingnya penjelasan memadai mengenai besaran tarif denda untuk sektor pertambangan. Salah satunya adalah perbandingan dengan tarif denda tunggal untuk perkebunan kelapa sawit yang hanya Rp 25 juta per hektar seperti tercantum pada PP Nomor 45 Tahun 2025. Ancaman denda yang sangat besar tersebut berisiko menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan.
Ketentuan yang hanya mendasarkan pada sektor usaha dan juga jenis komoditas pada pertambangan juga menimbulkan pertanyaan. Apakah rasionalitas yang mendasari sehingga besaran denda tergantung pada sektor usaha dan jenis komoditas, bukan berdasarkan tingkat kerusakan atau dampak lingkungan yang muncul akibat pelanggaran di kawasan hutan dimaksud. Ancaman denda dengan disparitas yang besar dan kebelumjelasan aturan jangan pula membuka celah “kompromi” yang bisa dimanfaatkan oleh otoritas tanpa integritas.
Pada akhirnya, pintu pemerintah sebagai petugas negara perlu terus diketuk untuk menegaskan fungsinya sebagai “pembina” keberlangsungan tata kelola negara, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya alam. Satgas PKH dan juga tarif ancaman denda yang tinggi, tidak perlu lahir andaikan pembinaan terhadap pelaku usaha berjalan dengan baik, termasuk monitoring dan evaluasi secara berkala. Kebijakan tidak boleh bermimikri menjadi penghukuman semata. Kebijakan tak boleh hanya melahirkan ketakutan oleh rezim pemberi izin dan penerbit denda.
*Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dan lulusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB)