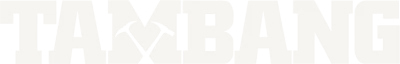Oleh : Ferdy Hasiman *
Sejak 1 Januari, 2014, pemerintah melarang semua perusahaan tambang mineral, tembaga, emas, perak, bauksit, nikel dan mangan mengekspor mineral mentah dengan harga rendah. Tambang ekstraktif seperti itu lebih banyak merusak lingkungan, tak memiliki efek pelipatan bagi pembangunan dan hanya membutuhkan pekerja kasar. Melalui UU No.4 Tahun 2009, Tentang Mineral dan Batubara yang sudah direvisi menjadi UU No.3 Tahun 2020 dan direvisi lagi menjadi UU No.2 Tahun 2025, semua perusahaan tambang wajib membangun produk hilir. Artinya, perusahaan tambang wajib membangun pabrik smelter agar harganya lebih tinggi, ada efek peliputan pembangunan dan penerimaan negara meningkat.
Semua perusahaan tambang kemudian berlomba-lomba membangunan smelter, karena jika tidak, mereka tak boleh mengekspor mineral mentah. Perusahaan-perusahaan nikel Tiongkok yang beroperasi di Sulawesi Tengah dan Halmahera adalah yang paling ekspansif. Selain itu, BUMN tambang anggota Holding MIND ID juga tak kalah cekat mengejar hilirisasasi produk tambang. Menurut Forum Nikel Indonesia (2020), sudah ada 23 pabrik smelter nikel yang telah terpasang dengan total kapasitas 3,7 juta ton NPI. Smelter-smelter itu banyak berlokasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
Di nikel, PT Sulawesi Mining Investment (SMI) misalnya sudah sejak tahun 2015 telah pabrik smelter berkapasitas 300.000 ton per tahu ferronickel dengan pembangkit listrik sebesar 2×65 MW. Anak usaha IMIP lainya, PT Indonesia Guang Ching and Stainless Steel Industry (GCNS) juga membangun smelter feronikel berkapasitas 600.000 ton per tahun di Sulawesi Tengah dengan dana pinjaman sebesar US$700 juta dari Eksport-Import Bank Of China, Bank of China dan ICBC. Selain itu, PT Indonesia Tshingshan Stainless Steel (ITSS) juga membangun smelter berkapsitas 300,000 ton per tahun ferronickle, 1 juta ton per tahun stainless steel.
Sementara untuk BUMN tambang, MIND ID benar-benar menjadi penopang hilirisasi pemerintah dengan membangun proyek hilir. Anggota holding MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk misalnya menambah ekspansi pengembangan smelter Feronikel Halmahera Timur (FeniHaltim) berkapasitas 13.000 matrik ton dan beroperasi tahun 2024. Ini menambah daya dobrak ANTM, karena perusahaan ini telah lama membangun pabrik smelter Feronikel berkapasitas 27.000 matrik ton di Kolaka, Sulawesi Tenggara tahun 1973. Sementara anggota MIND ID lainnya Indonesia Asahan Alumina telah lama memproduksi bauksit menjadi alumina ingot sebesar 500.000 ton, terbesar di Asia. INALUM dan ANTM juga ID juga sudah memulai proyek SGAR di Tayan, Kalimantan Tengah dengan produksi 1 juta ton alumina per tahun.
Sementara untuk produsen tembaga, PT Freeport Indonesia telah memproduksi konsentrat tembaga di Manyar dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahun dan PT Amman Mineral Tbk sedang menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di Sumbawa Barat dengan kapasitas 900.000 matrik ton per tahun. Menurut data, dua produsen tembaga di tanah air ini mampu menghasilkan cathode tembaga sebesar 1.5 juta ton per tahun dan menjadi ke-empat terbesar di dunia, dibelakang Cina (12 juta), Kanada (2 Juta) dan Brasil (1,7 juta).
Hanya Sebatas Produk Antara
Dengan melihat fakta di atas, semua perusahaan tambang hampir sudah taat menjalankan perintah konstitusi, membangun produk hilir dengan membangun pabrik smelter. Meskipun demikian, produk hilir itu barulah produk antara. Karena harus ada industri kuat yang bisa menyerap semua produk dari perusahaan tambang. Indonesia misalnya, belum memiliki pabrik stainless steel yang akan menyerap produk feronikel dari perusahaan-perusahaan nikel yang sudah membangun smelter. Jika pabrik stainlees steel tak dibangun, paling banter, produk-produk Feronikel yang diproduksi perusahaan-perusahaan nikel harus diekspor, karena daya serap dalam negeri rendah.
Industri pertambangan penting sebagai penopang backbone industrialisasi. Industri penerbangan misalnya, hanya bisa hidup, jika pabrik aluminia milik ANTM dan INALUM yang dibangun di Tayan, Kalimantan bisa terealisasi. Selain itu, industri penerbangan memerlukan baja. Indonesia tak kekurangan stock nikel, baja, biji besi, untuk membangun industri penerbangan kelas dunia. Coba bayangkan, bagaimana jika perusahaan penerbangan PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Bandung itu dikelolah secara profesional, diperlengkapi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia mupuni dibidangnya.
Bukan hanya itu, industri penerbangan hanya bisa hidup jika ditopang sektor industri pertambangan sebagai bahan baku. Kita juga tak kekurangan hasil baja. Perusahaan milik negara, PT Kerakatau Steel adalah produsen penghasil baja terbesar dunia. Namun, selama ini produksi baja tak bisa diolah di dalam negeri. Kita mengekspor baja besar-besaran ke luar dan membeli lagi hasil olahan baja untuk kepentingan industri domestik. Sebelum tahun 2014, Indonesia menjadi sumber untuk penjualan bahan mentah tambang ke Cina untuk industri manufaktur di negeri itu. Kebijakan pemerintah melarang ekspor mineral mentah berpengaruh besar pada pemain-pemain alumnium, baja, nikel, bauksit dan tembaga di negara-negara industri maju.
Di industri otomotif, bahan tambang adalah tulang punggung kemajuan industri itu. Apalagi dengan kampanye transisi energi global dan nasional, mestinya menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang yang sudah membangun fasilitas smelter. Untuk kendaraan listrik misalnya, mereka membutuhkan baterai kendaraan listrik sebagai penopang. Untuk pembangunan baterai kendaraan listrik, mineral penting yang dibutuhkan, seperti tembaga (10,8 persen), aluminium (18.9 persen), nikel (15,7 persen), baja (10,8 persen), mangan (5,4 persen), cobalt (4,3 persen) dan lithium (3,2 persen). Ini tentu menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang.
Glencore, salah satu produsen metal terbesar dunia mengatakan, kebijakan kendaraan listrik akan menambah permintaan (demand ) tembaga sebesar 18 persen tahun 2030. Sementara permintaan nikel global akan tumbuh 55 persen tahun 2030. Dalam ekosistem kendaraan listrik, tembaga digunakan untuk pembangunan jaringan listrik, jaringan storage (penyimpanan/reservoar) dan charging (Infrastrukur pengisian). Menurut Glencore, permintaan tembaga untuk charging saja, misalnya akan tumbuh dari 23,000 ton di tahun 2020 menjadi 392,000 ton tahun 2030. Ini tentu berita baik bagi produsen tembaga, seperti PT Freeport Indonesia yang telah membangun pabrik smelter tembaga di Manyar, Jawa Timur dan Amman Mineral di Sumbawa Barat. Dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, hasil olahan tembaga mudah terserap.
Produsen tambang Indonesia akan mendapat untung besar dengan melihat trend global ke kendaraan listrik. China Association Of Automobile Manufactures (CAAM:2019) mengatakan, sejak tahun 2019, kendaraan listrik di Cina tumbuh 1.7 juta unit dari 1.6 juta unit tahun 2018. Sementara penjualan mobil berbasis fosil di Cina mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2019, penjualan mobil berbasis fosil Cina turun 13 persen atau 4.82 juta unit per tahun, sementara penjualan kendaraan listrik meningkat 118 persen menjadi 254.000. Sementara, McKinsey (2022) memproyeksikan, produksi mobil listrik global tumbuh dari 20 juta unit tahun 2025. Menurut International Energy Agency (IEA) pertumbuhan 20 juta kendaraan listrik itu membutuhkan sekitar 80 kg tembaga untuk memenuhi kebutuhan kabel, motor, dan baterai EV, serta sekitar 23 kg untuk mobil tradisional.
Meskipun demikian, mayoritas produk perusahaan tambang yang diolah di smelter belum terserap maksimal di pasar domestik. Produsen-produsen tembaga misalnya, mengatakan bahwa serapan hasil olahan tembaga dalam negeri Hanya 30 persen dan sisanya 70 persen harus diekspor. Itu diserap produsen petrokimia. PT Petrokimia Gresik misalnya, adalah salah satu perusahaan yang menyerap produk smelter Freeport Sulfurid acid sebesar 1,7 juta ton per tahun untuk kepentingan industri pupuk di tanah air. Mestinya, jika pemerintah mendorong swasembada pangan, produksi perusahaan-perusahaan pupuk meningkat dan penyerapan produk olahan smelter tembaga akan samakin besar. ANTM juga menyerap olahan tembaga untuk emas Batangan Freeport dari Manyar. Ini penting agar mengurangi impor bahan baku emas Batangan dari Singapura.

Ini terjadi karena Indonesia belum bersiap masuk ke industri. Pabrik baterai kendaraan listrik misalnya, belum juga dibangun sampai sakarang. Padahal, jika itu berjalan, serapan nikel, timah, tembaga dan alumina akan lebih besar. Di tengah gerakan global melaksanakan transisi energi, kebutuhan nikel baik sebagai bahan baku baja maupun nikel kadar rendah dengan kandungan kobalt menjadi bahan baku penting untuk produksi baterai berbasis Nickel-Mangan-Cobalt(NMC). Indonesia juga bisa menjadi pemain utama di industri aluminium global. Dengan cadangan yang masih besar, produksi alumina dan aluminium masih bisa ditingkatkan. Di saat perusahaan swasta masih sulit membangun refinery bauksit maka tumpuan utama saat ini ada pada perusahaan plat merah. Institute Aluminium Internasional (IAI) menyebutkan permintaan aluminium global akan meningkat 40 persen pada 2030. Kenaikan ini ditopang oleh sektor transportasi, konstruksi, pengemasan dan kelistrikan.
Jadi, pemerintah harus mulai memikirkan desain industrialisasi dan menerapkan kebijakan keberpihakan terhadap prorduk-produk tambang nasional. Anggota holding MIND ID, PT TimahTbk misalnya memiliki segalanya menjadi terbesar. Perusahaan dengan Sejarah penambangan yang panjang ini merupakan produsen terbesar logam timah di Indonesia dan merupakan produsen kedua terbesar dunia, setelah Yunan Tin China. Timah juga telah membangun pabrik pengolahan pabrik pengolahan logam timah lewat anak usahanya PT Timah Industri yang menghasilkan tin chemical, tin pellet dan tin solder. Sayangnya, produk PT Timah ini tidak mendapat perhatian khusus pemerintah. Produk tin plate yang dihasilkan PT Timah Industri masih kalah bersaing dengan produk impor. Ini terjadi bukan karena kualitas, tetapi karena harga produk impornya lebih murah setelah tidak dikenakan bea impor.
Peta-Jalan Industrialisasi
Pemerintah perlu mendesain peta jalan yang jelas dari hilirisasi. Pemerintah perlu mempercepat perijinan dan insentif untuk hilirasi mineral. Ini perlu dilakukan pemerintah pusat-daerah untuk menyederhanakan proses perijinan bagi perusahaan yang bangun smelter. Apalagi jika itu dilakukan perusahaan negara, seperti anggota holding MIND ID. Selain itu pemerintah perlu memberikan insentif berupa tax holiday untuk investasi hilirisasi. Itu akan mempercepat ekosistem industri terbentuk. Jika ekosistem itu terbentuk, serapan lapangan kerja akan menjadi sangat besar.
Harus diakui bahwa sampai sekarang produk yang dihasilkan masih merupakan produk antara. Hasil dari pengolahan dan pemurnian yang dilakukan dalam negeri kemudian diekspor. Ke depan yang harus didorong adalah bagaimana membangun industri penyerap produk-produk antara tersebut untuk menghasilkan produk-produk lebih ke hilir. Nilai tambah yang dihasilkan akan lebih dari yang didapat sekarang. Produk timah misalnya ke depan akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik dan industri elektronik. Timah juga dibutuhkan di panel surya dan teknologi energi terbarukan lainnya. Timah juga menjadi bahan utama dalam produksi semikonduktor, yang sangat penting bagi banyak perangkat elektronik dan sistem AI.
Demikian juga dengan tembaga yang prospeknya semakin mengkilap ke depan. Ini terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Tembaga bahkan disebut sebut mengalami proses transformasi yang signifikan dengan meningkatnya permintaan yang didorong oleh transisi energi dan faktor-faktor lain sementara dari sisi pasokan masih mengalami kendala. Ketidakseimbangan ini kemungkinan akan menyebabkan defisit tembaga, kenaikan harga, dan peluang potensial untuk investasi di sektor ini.
Kemudian keberpihakan Pemerintah pada setiap program hilirisasi juga harus jelas. Apalagi jika itu dilakukan oleh BUMN yang adalah perusahaan milik negara. Keberpihakan ini bisa dilakukan lewat insentif yang diberikan sehingga semakin ekonomis. Sebut saja untuk tembaga dan bauksit yang nilai investasinya cukup besar.
* Pengamat Energi dan Pertambangan