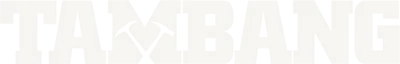JAKARTA–TAMBANG. KAMIS pekan lalu (18 Desember), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini merupakan pertemuan akbar yang dihadiri para bupati, gubernur, menteri, yang membicarakan rencana kegiatan pembangunan di Indonesia.
Di depan para kepala daerah, Presiden Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tak bangga dengan hasil sumber daya alam.
Jokowi mengatakan, tiap kali blusukan, banyak kepala daerah yang membangga-banggakan hasil buminya. Mulai dari kelapa sawit, batu bara, dan gas. Padahal, kata Jokowi, negara maju tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya. Karena, kalau sumber daya alam itu tak dikelola dengan tepat, malah akan jadi malapetaka.
Menurut Jokowi, yang diperlukan untuk menjadi negara maju adalah kebijakan publik yang baik dan tepat. Dia menyebut, Jepang dan Singapura sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi negara maju meski tak memiliki kekayaan alam. “Kuncinya ada di bapak ibu semua. Kunci kebijakan publik yang benar dan tepat. Kalau ada kebijakan publik yang tepat akan majulah sebuah negara,” katanya.
Jokowi mengambil contoh, orang Indonesia sering menyebut dirinya sebagai bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Namun kenyataannya hampir semua bahan pangan impor, mulai dari beras, gula, kedelai, dan jagung. Padahal, Indonesia adalah negara agraris. Jokowi menilai, hal ini terjadi karena kebijakan publik yang salah.
***
Peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi secara terbuka, tanpa tedeng aling-aling, merupakan hal penting kita garis bawahi. Kita sering mendengar adanya kabupaten atau provinsi hasil pemekaran yang ternyata malah jadi lebih miskin, justru setelah menjadi daerah otonomi baru.
Kita juga sering melihat di berbagai daerah, kabupaten atau provinsi yang kaya minyak, tetapi jalannya berlobang-lobang. Kekayaan alam hanya dinikmati segelintir penguasa, kerabat, dan kroninya.
Sejak kecil kita sering dilenakan oleh berbagai jargon yang mengatakan bahwa kita hidup di negara yang semuanya serba wah. Lihat saja: negara selalu disebut sangat strategis, karena terletak di persilangan dua benua, dan persilangan dua samudera. Musisi Koes Plus menyebut betapa subur Indonesia, sehingga tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman.
Masalahnya, lokasi Indonesia yang strategis itu ternyata kurang memberi manfaat ekonomi, karena kapal dagang lebih banyak berhenti di Singapura ketimbang meneruskan perjalanannya ke Jakarta. Turis Eropa yang ke Thailand, Malaysia, dan ke Singapura, juga lebih banyak ketimbang yang melawat ke Indonesia. Bila ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’, kenapa kita mesti mengimpor beras, kedelai, dan kentang? Presiden Jokowi mengatakan, itu semua karena kebijakan publik yang salah.
Saya sependapat dengan kalimat itu. Kebijakan publik memang sangat menentukan. Sebagai contoh, bertahun-tahun kita dibuat senang karena selalu mendapatkan bensin dan solar dengan harga murah. Akibatnya, ratusan triliun duit negara selalu dibakar, setiap tahunnya, demi subsidi BBM, agar harga bensin dan solar murah. Padahal, setelah harga premium dan solar dinaikkan Rp 2.000 per liter, pemerintah memiliki duit sangat besar untuk pembangunan jalan, dermaga, dan kesehatan.
Harga BBM yang murah membuat kita tidak bersyukur. Sebagian nelayan yang mendapatkan minyak bersubsidi itu malah menjual bahan bakarnya di tengah laut, ke kapal-kapal asing. Dari selisih harga minyak itu saja ia bisa mendapatkan Rp 80 juta.
Di bidang pertambangan, selama puluhan tahun kita hanya menjual bahan mentah, tanpa berusaha mengolahnya di dalam negeri. Jutaan ton tanah mengandung mineral setiap tahun diangkut ke luar negeri. Syukurlah, sejak 2014 ini kewajiban mengolah hasil tambang di dalam negeri dilaksanakan.
Bahkan yang dilakukan Indonesia dengan melarang ekspor mineral mentah, akan diikuti sejumlah negara. Filipina, dan sejumlah negara di Afrika, tengah membicarakan peraturan yang mirip dengan Indonesia, yang mewajibkan pengolahan mineral di dalam negeri.
Kekayaan alam yang ada di bumi kita memang tak boleh kita sombongkan, dan kita nikmati dengan tanpa kehati-hatian.
Anda tentu masih ingat dengan Nauru, sebuah pulau kecil dengan luas 21 kilometer persegi, dan berpenduduk kurang dari 10.000 jiwa. Pulau di Samudera Pasifik bagian selatan ini terkenal karena fosfatnya. Pada 1960-1970, pendapatan per kapita warganya terdongkrak tinggi, sejajar dengan negara maju lainnya, karena hasil mengeruk fosfat. Pada era itu warganya gemar berkeliling dunia, untuk berfoya-foya.
Fosfat di Nauru dikenal gampang ditambang, karena terletak di permukaan. Kualitasnya juga bagus. Dengan pulau yang luasnya tak lebih dari sebuah kelurahan di Bekasi, penambangan fosfat sangat mengganggu lingkungan, dan mengancam kelangsungan pulau. Apalagi fosfat merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Pada 2011, fosfat di Nauru dinyatakan tak layak lagi ditambang.
Nauru lalu mengubah dirinya sebagai negara yang menyediakan fasilitas penyimpanan uang bebas pajak, juga tempat untuk menampung duit rekening yang dijamin kerahasiaannya. Maka, duit hasil penjualan narkoba, korupsi, pun mengalir. Kini, kehidupan Nauru banyak tergantung pada bantuan dari Australia. Sebagai imbalan, Nauru menyediakan tempat penampungan bagi para pengungsi atau pencari suaka yang mau menjadi warga Australia.
***
Di buku ‘’Syukur Tiada Akhir’’ yang berisi jejak langkah pemikiran tokoh pers Indonesia, Jakob Oetama, ada bagian menarik di bab 6, bab yang berjudul ‘’Belajar dari Cina dan India’’. Di situ, Jakob menyinggung Korea Selatan yang memiliki budaya saemaul undong. Dengan budaya itu, Korea Selatan berkembang 30 kali lipat, hanya dalam waktu 10 tahun, dibandingkan dengan Ghana. Ia mencontohkan bagaimana Korea Selatan yang memiliki budaya hemat, rajin menabung, serta kerja keras, dapat meloncat jauh meninggalkan Ghana yang memiliki budaya malas-malasan, boros dan tidak rajin menabung.
Lebih jelas mengenai hal itu bisa dilihat di buku ‘’Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Manusia’’, yang pengantarnya ditulis oleh pemikir kondang Samuel P. Huntington.
Di situ, ia menulis, ‘’Di awal tahun 1990-an, secara kebetulan saya menjumpai data ekonomi Ghana dan Korea Selatan tahun 1960-an awal. Saya takjub melihat betapa miripnya ekonomi dua negara ini pada waktu itu. Dua negara ini, kira-kira, memiliki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang setara; porsi ekonomi mereka yang serupa antara produk, manufakturing, dan jasa primer; serta berlimpahnya ekspor produk primer, dengan Korea Selatan memproduksi sejumlah kecil barang manufaktur. Mereka juga menerima bantuan ekonomi dalam jumlah yang seimbang.’’
Lanjutnya, ‘’Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa industri ekonomi terbesar nomor ke-14 dunia, perusahaan-perusahaan multinasional, ekspor mobil, alat elektronik, dan barang canggih hasil pabrik lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan perkapita yang mendekati Yunani. Tidak ada perubahan seperti ini di Ghana, yang PDB per kapitanya sekarang sekitar seperlimabelas dari Korea Selatan.’’ Korea Selatan bahkan kini sudah melampaui Yunani.
Korea Selatan, demikian pula Jepang dan Singapura, jelas bukan negara yang berlimpah dengan kekayaan alamnya. Tetapi tiga negara ini sukses memanfaatkan kepintaran otak warganya, serta cerdas dalam menentukan kebijakan publik.
Era mengandalkan kekayaan alam memang sudah berlalu. Kita sudah lama berada di era yang menuntut kita mengandalkan kepintaran dan kejujuran.
Foto: penambangan fosfat di Nauru. Sumber: http://www.stephencodrington.com/