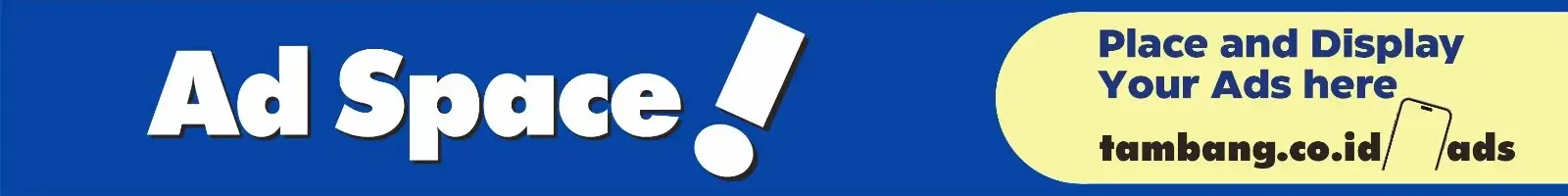Harga Nikel Global Turun, APNI Harap Pemerintah Evaluasi Ulang Aturan Tarif Royalti Baru

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap pemerintah mengevaluasi ulang Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kenaikan tarif royalti baru sektor ESDM. Hal ini lantaran harga nikel global tengah mengalami penurunan tajam akibat ketegangan geopolitik.
“Kebijakan ini dinilai kurang tepat waktunya, mengingat harga nikel global tengah mengalami penurunan tajam akibat ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) APNI, Meidy Katrin Lengkey dalam keterangannya, Rabu (16/4).
Meidy menilai, kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut akan menambah beban industri nikel domestik baik untuk pemain hulu maupun hilir. Kebijakan ini juga berisiko mengurangi daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian domestik.
“Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir, dan berisiko mengurangi daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” imbuh Meidy.
Tarif royalti baru tertuang dalam PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 11 April 2025.
Pemerintah Keluarkan Regulasi PNBP Bidang ESDM, Intip Kenaikan Sektor Minerba
Meidy menyampaikan dasar keberatan pengenaan tarif PNBP baru yang dinilainya tidak realistis dan tidak progresif. Kata dia, kenaikan tarif royalti untuk bijih nikel yang mencapai 14-19% dan produk olahan seperti FeNi/NPI yang mencapai 5-7% dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil industri:
“Harga nikel global terus mengalami penurunan. Contoh harga LME turun [X]% dalam 12 bulan terakhir, sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis. Biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR +6.5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan,” jelasnya.
Tak hanya itu, keberatan juga didasarkan terhadap investasi smelter yang padat modal dan resiko tinggi, dengan biaya pembangunan mencapai USD1,5-2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (Global Minimum Tax 15%).
“Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” imbuh dia.
Lebih jauh, Meidy menjelaskan bahwa industri saat ini menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi DAS.
Kenaikan royalti juga menurutnya berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu-hilir nikel, menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global, dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
“Kenaikan tarif royalti yang menekan margin produksi akan memaksa penambang meningkatkan cut off grade, sehingga volume cadangan akan menyusut signifikan. Dengan cadangan yang menyusut, tingkat produksi dan life,” jelas dia.
Meidy menyebut bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM memang mengundang APNI untuk membahas perubahan kebijakan tarif PNBP ini.
“Pada 17 April 2025, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM juga mengundang APNI dan FINI untuk membahas rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme penjualan dan perhitungan nilai mineral,” ucapnya.
Sebagai alternatif solusi yang konkret, APNI mendorong pemerintah untuk merevisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel, ferronickel, dan nickel pig iron (NPI). Saat ini, formula HPM dinilai terlalu rendah dibandingkan indeks harga pasar seperti Shanghai Metals Market (SMM), sehingga dalam dua tahun terakhir berpotensi menyebabkan kerugian nilai pasar hingga 6,3 miliar USD.
“APNI mengusulkan agar formula HPM diperbarui dengan memasukkan nilai keekonomian dari kandungan besi pada bijih saprolit dan kobalt pada bijih limonit, yang selama ini belum dimonetisasi. Estimasi menunjukkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan HPM hingga lebih dari 100%, tergantung karakteristik bijih dan efisiensi ekstraksi,” pungkas dia.