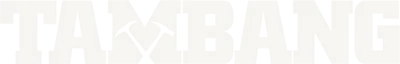* Jalal
SEBAGAI seorang profesional yang telah mendedikasikan puluhan tahun hidup saya untuk mengamati simpangan yang seringkali penuh gejolak antara industri ekstraktif dan tatanan sosial masyarakat, saya merasa wajib memberikan apresiasi yang mendalam terhadap karya Kristina Großmann dan Ajarani Mangkujati Djandam. Bab yang mereka tuliskan, Reconfigurations of Asymmetries in Mining in Indonesia, sebagai bagian dari bunga rampai anyar Ecological Interdependencies: Strong Asymmetrical Relations and More-than-Human Worlds yang disunting oleh Zeynep Gökçe and Jennifer Leetsch benar-benar menyajikan sebuah analisis yang tajam, kaya secara etnografis, dan sangat penting di tengah diskursus global mengenai sumberdaya alam.
Begitu selesai membacanya, saya menyadari bahwa karya ini merupakan sumbangan signifikan yang melampaui narasi biner sederhana tentang ‘perusahaan jahat’ versus ‘komunitas korban’ yang sering mendominasi wacana publik, termasuk yang kerap ditulis oleh para akademisi di Indonesia. Sebaliknya, para penulis dengan cermat membedah bagaimana operasi pertambangan skala besar tidak mendarat di ruang sosial yang hampa, melainkan masuk dan secara aktif berinteraksi dengan hierarki, jaringan patronase, dan ketimpangan yang telah ada sebelumnya.
Karya Etnografis yang Mengagumkan
Apresiasi saya yang pertama tertuju pada pilihan kerangka konseptual mereka. Penggunaan lensa dependensi asimetris (asymmetrical dependency) sangatlah tepat. Konsep ini, yang didefinisikan sebagai relasi sosial di mana satu pihak tidak memiliki prospek untuk mengubah atau keluar dari hubungan ketergantungan karena konteks politik, sosial, atau ekonomi, memberikan ketajaman analitis yang lebih presisi daripada sekadar istilah ‘ketimpangan’ yang dominan dipakai.
Konsep yang mereka pakai itu jelas menangkap esensi dari apa yang terjadi di banyak komunitas tambang dengan lebih baik. Lebih lanjut, upaya mereka untuk memerluas pemahaman interseksionalitas—melampaui kategori standar kelas, ras, dan gender—untuk mencakup kategori yang relevan secara lokal seperti garis keturunan (lineage) dan kebangsawanan (nobility) adalah sebuah langkah metodologis yang brilian. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang konteks Asia Tenggara, di mana bentuk-bentuk demarkasi sosial ini seringkali jauh lebih berpengaruh daripada di konteks Barat.
Kekuatan luar biasa lainnya datang dari desain komparatifnya yang cerdas antara dua studi kasus di Kalimantan. Tumbang Batubara dan Long Maas tidak disajikan secara terpisah, tetapi digunakan sebagai kontras yang kuat untuk menyoroti tesis utama para penulis: bahwa pertambangan dapat memperkuat sekaligus mengkonfigurasi ulang asimetri yang ada. Di Tumbang Batubara, kita melihat studi kasus klasik tentang ‘penyemenan’ (cementation) kekuasaan. Para penulis secara meyakinkan menunjukkan bagaimana perusahaan tambang batubara Adaro Met Coal secara strategis menjalin jaringan patronase dengan elite desa yang ada, yang kekuasaannya didasarkan pada garis keturunan dari pendiri desa, Damang Wulang. Mekanisme kontrol ini diekspos dengan gamblang melalui analisis negosiasi kompensasi lahan, di mana elite desa menjadi perantara eksklusif, seringkali dengan mengorbankan warga biasa. Pengamatan bahwa elite ini menggunakan taktik suap dan ancaman, sambil secara retoris membenarkan tindakan mereka sebagai tanggung jawab patron atau menyalahkan patron mereka yang lebih tinggi (bupati), adalah detail etnografis yang kaya dan mengungkap cara kerja patronase modern yang saya saksikan wujudnya di berbagai pelosok Indonesia.
Sebaliknya, kasus Long Maas menyajikan gambaran yang jauh lebih dinamis dan, bisa dibilang, lebih penuh harapan, yang menyoroti inti dari argumen ‘rekonfigurasi’. Di sini, struktur hierarkis didasarkan pada kebangsawanan (dibedakan antara “orang keturunan” dan “orang biasa”). Analisis para penulis tentang dampak ganda dari tambang emas PT KEM sangatlah tajam. Di satu sisi, perusahaan awalnya memerkuat elite bangsawan dengan memberi mereka prioritas pekerjaan, terlepas dari kualifikasi. Hal ini memberi mereka modal finansial untuk memerluas karir politik mereka, seperti dalam kasus Ingan dan Adip. Namun, dan ini adalah poin krusial, perusahaan secara bersamaan memerkenalkan ‘budaya korporat’ baru kepada seluruh masyarakat. Logika baru ini—yang didasarkan pada pendidikan, keterampilan, dan kinerja kerja—membuka celah bagi mobilitas sosial bagi siapapun, bukan hanya para bangsawan.
Di sinilah letak temuan paling menarik dari bab ini: munculnya orang kaya baru yang terdidik atau the new educated rich. Kisah Ampong, yang berasal dari keluarga biasa namun berhasil memanfaatkan program pelatihan dan peluang di perusahaan untuk membangun karir dan kekayaan adalah ilustrasi sempurna dari proses ini. Para penulis dengan tepat mengidentifikasi bahwa ini bukan hanya perubahan ekonomi di tingkat individu, melainkan sebuah pergeseran sosiopolitik. Orang-orang kaya baru ini, yang mendapat legitimasi melalui kontribusi finansial mereka pada pembangunan desa dan keterampilan manajerial yang dianggap lebih profesional, kini dapat menantang monopoli politik kaum bangsawan yang selama beberapa dekade, atau bahkan abad, seperti tak tertantang. Fakta bahwa posisi kepala desa sekarang terbuka untuk kompetisi, meskipun posisi kepala adat tetap dipegang oleh bangsawan, menunjukkan rekonfigurasi kekuasaan yang tidak paripurna, namun jelas tidak dapat disangkal. Ini adalah sebuah nuansa yang sangat penting yang disajikan dengan sangat baik.
Beberapa Catatan Kritis
Namun, saya juga ingin mengajukan pembacaan yang lebih kritis dan mendorong analisis lebih jauh berdasarkan apa yang saya pahami soal pertambangan dan masyarakat sekitarnya di Indonesia. Karenanya, meskipun karya ini luar biasa, saya perlu menyatakan masih ada beberapa dimensi yang menurut saya dapat dieksplorasi lebih dalam untuk memerkuat argumennya atau membuka jalan bagi penelitian di masa depan.
Pertama, peran Negara terasa agak kabur di latar belakang. Para penulis menyebutkan rezim Orde Baru dan bagaimana rezim tersebut memerkuat patronase, serta menyebutkan bupati sebagai patron bagi elite desa di Tumbang Batubara. Namun, analisis ini kurang mendalami dampak dari salah satu reformasi politik terpenting di Indonesia pasca-1998: desentralisasi atau otonomi daerah. Teks ini hanya menyebutkannya sekali secara singkat. Padahal, desentralisasi secara fundamental mengubah lanskap industri ekstraktif dengan mentransfer kekuasaan perizinan dan pengawasan ke tingkat kabupaten/kota. Bagaimana dinamika otonomi daerah ini berinteraksi dengan jaringan patronase lokal? Mungkinkah ‘penyemenan’ kekuasaan di Tumbang Batubara justru difasilitasi oleh struktur otonomi daerah yang ditangkap oleh elite lokal? Dan sebaliknya, mungkinkah reformasi yang sama di Long Maas, yang dikombinasikan dengan modal dari para orang kaya baru itu, yang memungkinkan penantangan terhadap bangsawan? Ini saya bayangkan sebagai variabel antara yang krusial yang perlu diartikulasikan dengan lebih jelas.
Kedua, ada perbedaan temporal dan operasional yang signifikan antara kedua studi kasus yang mungkin perlu digali lebih jauh. Studi kasus Tumbang Batubara berfokus pada projek Adaro Met Coal yang sedang beroperasi dan berkembang. Sebaliknya, studi kasus Long Maas berfokus pada tambang PT KEM yang berhenti berproduksi pada tahun 2003 dan ditutup secara resmi pada tahun 2005—dua dekade lampau. Ini adalah perbedaan kontekstual yang sangat besar. Munculnya orang kaya baru di Long Maas dan keberhasilan mereka dalam arena politik desa mungkin sebagian besar difasilitasi oleh perginya patron perusahaan utama. Dengan kata lain, mungkin sekali rekonfigurasi kekuasaan terjadi dalam kekosongan yang ditinggalkan pascatambang. Apakah rekonfigurasi serupa mungkin terjadi di Tumbang Batubara jika tambang Adaro masih beroperasi penuh dan secara aktif menopang elite garis keturunan? Membandingkan tambang yang aktif dengan yang pasca-operasional mungkin agak mirip membandingkan apel dan jeruk. Analisis yang lebih eksplisit tentang bagaimana fase siklus hidup tambang (eksplorasi, operasi, penutupan, dan pascatambang) memediasi rekonfigurasi asimetri akan sangat memerkaya argumen.
Ketiga, saya ingin mengomentari optimisme tersirat seputar para orang kaya baru di Long Maas. Para penulis menggambarkan mereka sebagai kekuatan penyeimbang yang menantang hierarki tradisional dan memerintah secara lebih profesional. Ini, tentu saja, adalah pengamatan etnografis yang valid. Namun, dari perspektif kritis studi agraria dan patronase, agaknya kita juga perlu bertanya: apakah ini benar-benar disrupsi terhadap asimetri, atau hanya penggantian satu bentuk patronase dengan bentuk lainnya? Ampong dan rekan-rekannya menggunakan kekayaan mereka untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pendidikan—yang adalah taktik klasik dalam membangun basis klien dalam patronase. Apakah para orang kaya baru ini pada akhirnya hanya akan menjadi patron baru, yang legitimasinya didasarkan pada modal finansial dan keterampilan manajerial, bukan garis keturunan? Sehingga, kita bisa juga bertanya apakah ‘dependensi asimetris’ benar-benar berkurang, atau hanya berganti aktor dan wajah, dari patron berbasis garis keturunan menjadi patron berbasis modal? Studi jangka panjang agaknya diperlukan untuk melihat apakah elite baru ini menciptakan tatanan yang lebih inklusif atau sekadar mereplikasi struktur patron-klien lama dengan perangkat dan retorika baru.
Terakhir, saya merasa bahwa konsep ‘perusahaan’ itu sendiri diperlakukan agak monolitik. Kita bisa membaca tentang bagaimana ‘perusahaan’ bernegosiasi dengan masyarakat, memrioritaskan pekerjaan untuk mereka yang dekat, dan membangun jaringan. Dalam praktiknya, saya menyaksikan bahwa perusahaan, terutama perusahaan multinasional atau konglomerat besar, bukanlah aktor tunggal. Mereka adalah arena kontestasi internal antar-departemen yang berbeda. Departemen Hubungan Masyarakat/CSR, Operasi, HRD, dan Logistik kerap hadir dengan kepentingan dan KPI-nya masing-masing yang seringkali bertentangan. Kasus Ingan di Long Maas, yang mendapat posisi di Departemen Logistik tanpa kualifikasi, menunjukkan bahwa satu departemen mungkin beroperasi di bawah logika patronase lokal, sementara departemen lain—mungkin didorong oleh ekspatriat atau manajemen pusat—mencoba menerapkan budaya perusahaan yang cenderung meritokratis. Membuka kotak hitam perusahaan dan menganalisa bagaimana ketegangan internal ini dimainkan di lapangan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana keputusan perekrutan dan alokasi sumber daya dibuat, yang pada gilirannya membentuk rekonfigurasi sosial di luar gerbang tambang.
*****
Tetapi, tentu saja, poin-poin tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai luar biasa dari karya Großmann dan Djandam. Sebaliknya, poin-poin ini adalah bukti bahwa teks mereka merangsang pemikiran dan percakapan akademis dan profesional yang mendalam. Makalah mereka memberikan model analisis etnografis yang luar biasa tentang bagaimana dampak sosial dari ekstraksi sumberdaya bukanlah naskah yang telah ditentukan hasilnya, melainkan sebuah proses yang dinamis, kontekstual, dan sangat bisa didiskusikan lebih jauh. Kedua penulis telah berhasil menunjukkan bahwa asimetri tidak hanya diberlakukan, tetapi dinegosiasikan, direproduksi, dan—yang paling penting—dikonfigurasi ulang oleh beragam aktor dengan modal sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.
Buat saya, ini adalah bacaan wajib bagi siapa pun yang tertarik pada studi pembangunan, ekologi politik, dan antropologi Indonesia modern. Dan untuk itu saya tak bisa tidak berterima kasih dan memberikan ucapan selamat yang tulus kepada kedua penulisnya.
* Provokator Keberlanjutan, Penulis Buku “Mengurai Benang Kusut Indonesia: Jokowinomics Di Bawah Cengkeram Korporasi” (2020) (Foto: Dok issf.or.id)