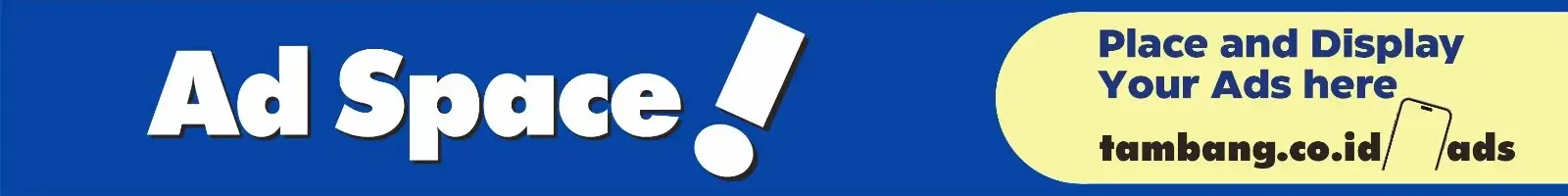Membedah Paradoks Ketergantungan: Pelajaran Dari Indeks Kontribusi Pertambangan Global 2025

Jalal *
Laporan Role of Mining in National Economies: Mining Contribution Index (7th Edition, 2025) yang dirilis oleh International Council on Mining and Metals (ICMM) tanggal 9 Oktober 29025 lalu menyajikan sebuah gambaran yang kompleks dan penuh nuansa mengenai peran sektor pertambangan dalam perekonomian nasional di seluruh dunia. Sebagai sebuah alat untuk memahami signifikansi kontribusi pertambangan, indeks ini bukanlah sekadar angka dan peringkat. Melainkan, ia membuka jendela ke dalam dinamika politik ekonomi yang mendasari ekstraksi sumberdaya mineral di level global dan nasional.
Analisis mendalam terhadap laporan ini mengungkap lima pelajaran penting yang menyoroti tren, tantangan, dan paradoks dalam lanskap pertambangan global saat ini. Selain itu, dengan menempatkan Indonesia dalam sorotan, kita dapat menarik dua pelajaran spesifik yang relevan bagi arah kebijakan sumberdaya negara ini ke depan.
Pelajaran pertama dan yang paling mendasar dari laporan ini adalah penguatan narasi ketergantungan akut negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terhadap sektor pertambangan. Laporan ini secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara di kategori ini mendominasi peringkat atas MCI, yang menandakan bahwa aktivitas pertambangan merupakan pendorong utama perekonomian mereka. Fenomena ini, yang konsisten dengan edisi-edisi sebelumnya, menggarisbawahi sebuah realitas yang penting sekaligus genting. Di satu sisi, pertambangan menyediakan sumber pendapatan ekspor dan aktivitas ekonomi yang vital, seperti yang terlihat pada negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo yang menduduki peringkat pertama, Mali di peringkat kedua, dan Zimbabwe di peringkat keempat.
Namun, di sisi lain, ketergantungan yang tinggi ini menciptakan kerentanan struktural terhadap fluktuasi harga komoditas global, pergeseran permintaan akibat transisi energi, dan guncangan geopolitik. Ketergantungan ini sering kali menghambat diversifikasi ekonomi, menjebak negara-negara dalam kutukan sumberdaya (resource curse) di mana kekayaan mineral tidak secara otomatis berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Laporan ini secara implisit mengingatkan bahwa skor MCI yang tinggi bukanlah lencana kehormatan, melainkan sebuah indikator yang memerlukan perhatian tata kelola yang serius untuk memastikan kekayaan di bawah tanah dapat ditranslasikan menjadi kemajuan di atas tanah.
Pelajaran kedua yang krusial adalah diskoneksi yang persisten antara kontribusi ekonomi pertambangan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Laporan MCI secara eksplisit menyatakan bahwa kontribusi ekonomi yang tinggi dari pertambangan tidak selalu konsisten dengan kemajuan material menuju SDGs atau tata kelola industri ekstraktif yang baik. Fakta bahwa 22 dari 25 negara teratas dalam peringkat MCI berada di paruh bawah indeks SDGs merupakan sebuah anomali yang mencemaskan. Ini adalah cerminan dari tantangan tata kelola keberlanjutan yang berat.
Kekayaan yang dihasilkan dari pertambangan memang seringkali gagal didistribusikan secara adil atau diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi fondasi SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka regulasi yang kuat, institusi yang transparan, dan kemauan politik yang kokoh, pendapatan dari pertambangan berisiko hanya memperkaya segelintir elite atau menguap melalui korupsi dan pengelolaan yang buruk. Inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) disebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong tata kelola yang lebih baik, namun laporan ini juga mengindikasikan bahwa kemajuan di bidang ini masih lambat dan belum merata di antara negara-negara yang paling bergantung pada pertambangan.
Pelajaran ketiga berkaitan dengan volatilitas dan sensitivitas peringkat terhadap perubahan metodologi dan dinamika pasar eksternal. Edisi ke-7 MCI mengalami perubahan metodologis yang signifikan, yaitu penghapusan indikator mineral rents karena ketiadaan data dari Bank Dunia untuk tahun 2022. Penghapusan ini, yang secara efektif meningkatkan bobot tiga indikator lainnya (kontribusi ekspor, perubahan kontribusi ekspor, dan nilai produksi terhadap PDB), telah menyebabkan pergeseran peringkat yang dramatis bagi banyak negara. Laporan ini sendiri mengakui bahwa perubahan ini menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar di peringkat atas dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
Ini memberikan pelajaran penting bahwa cara kita mengukur kontribusi pertambangan sangatlah subjektif dan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan data. Lebih jauh, hal ini menyoroti bagaimana guncangan eksternal, seperti rebound ekonomi pasca- COVID-19 dan peningkatan permintaan mineral untuk transisi energi, secara signifikan memengaruhi nilai produksi dan ekspor, yang pada gilirannya mengubah peringkat negara secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Ini juga menunjukkan betapa rapuhnya posisi suatu negara penghasil bahan tambang dalam hierarki pertambangan dan pengolahan hasilnya di tingkat global. Negara-negara ini sangat bergantung pada faktor-faktor di luar kendali mereka.
Pelajaran keempat adalah divergensi yang jelas antara nilai moneter produksi dan signifikansi ekonomi relatif. Laporan ini dengan cerdas menyajikan dua jenis peringkat: peringkat MCI utama yang mengukur kontribusi relatif terhadap perekonomian nasional, dan peringkat berdasarkan nilai produksi moneter absolut. Ketika dilihat dari nilai produksi absolut, peringkat didominasi oleh negara-negara berpenghasilan menengah-atas dan tinggi seperti Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, negara-negara berpenghasilan rendah yang mendominasi peringkat atas MCI justru berada di papan bawah dalam hal nilai produksi absolut.
Pemisahan ini sangatlah penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah negara mungkin bukan produsen mineral terbesar di dunia dalam volume ataupun nilai dolar, sektor pertambangan bisa jadi merupakan urat nadi perekonomiannya. Hal ini menekankan kembali pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan konteks. Bagi Australia, kebijakan pertambangan mungkin adalah salah satu dari banyak pilar ekonomi. Namun bagi Republik Demokratik Kongo, kebijakan pertambangan adalah kebijakan ekonomi fundamental yang menentukan nasib jutaan warganya. Kegagalan untuk memahami perbedaan ini dapat menyebabkan rekomendasi kebijakan yang tidak efektif atau bahkan berbahaya.
Pelajaran kelima yang dapat ditarik adalah pentingnya komponen dinamis dalam mengukur kontribusi pertambangan. Salah satu dari tiga indikator yang digunakan dalam MCI edisi ke-7 adalah “peningkatan/penurunan kontribusi ekspor mineral dan logam antara 2017-2022”. Indikator ini menambahkan dimensi waktu yang krusial, memungkinkan kita untuk melihat apakah peran pertambangan dalam sebuah ekonomi sedang tumbuh atau menyusut. Ini adalah sebuah wawasan yang tidak akan tertangkap jika kita hanya melihat potret sesaat (snapshot) dari data satu tahun. Negara-negara seperti Panama dan Niger, misalnya, menunjukkan lonjakan signifikan dalam perubahan kontribusi ekspor, yang mendorong peringkat mereka naik secara substansial. Komponen dinamis ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini, baik bagi negara yang ketergantungannya meningkat pesat—yang menandakan perlunya upaya diversifikasi yang lebih cepat—maupun bagi negara yang kontribusi pertambangannya menurun, yang mungkin memerlukan strategi transisi untuk tenaga kerja dan ekonomi lokal yang terkena dampak.
Sekarang, mari kita arahkan lensa analisis kita secara khusus ke Indonesia. Laporan MCI ini memberikan dua kesimpulan penting. Kesimpulan pertama adalah Indonesia telah muncul sebagai pemain pertambangan yang semakin signifikan baik secara absolut maupun relatif, namun dengan potensi jebakan ketergantungan yang perlu diwaspadai. Indonesia mengalami lonjakan peringkat yang sangat signifikan, naik 18 peringkat dari posisi 36 di edisi ke-6 menjadi posisi 18 di edisi ke-7. Kenaikan ini didorong oleh kinerja yang kuat di berbagai indikator, termasuk kontribusi ekspor sebesar 27,6% dan, yang lebih penting, nilai produksi mineral dan batubara sebagai persentase dari PDB yang mencapai 11,88%.
Secara nilai produksi absolut, posisi Indonesia bahkan lebih mengesankan, melompat ke peringkat 3 dunia dengan nilai produksi US$156,7 miliar, naik enam peringkat dari edisi sebelumnya. Ini agaknya mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi—meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam laporan—selain momentum harga komoditas yang menguntungkan. Namun, data ini juga membawa peringatan. Peningkatan pesat dalam kontribusi pertambangan terhadap ekonomi nasional menandakan peningkatan ketergantungan. Jika tidak diimbangi dengan penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya dan tata kelola yang transparan, Indonesia berisiko mengalami Dutch Disease, di mana lonjakan pendapatan dari sektor sumberdaya alam justru melemahkan sektor-sektor produktif lainnya seperti manufaktur dan pertanian.
Kesimpulan kedua yang spesifik untuk Indonesia adalah meskipun memiliki kekuatan produksi yang masif, peringkat kontribusi relatif Indonesia yang masih berada di luar 10 besar menunjukkan adanya skala ekonomi yang besar dan terdiversifikasi yang menjadi bantalan, sekaligus tantangan untuk optimalisasi. Peringkat Indonesia di posisi 18 pada MCI, meskipun meningkat tajam, masih berada di bawah negara-negara seperti Zambia, Tanzania, dan bahkan Afrika Selatan. Hal ini terjadi meskipun nilai produksi absolut Indonesia berkali-kali lipat lebih besar dari negara-negara tersebut.
Penjelasannya terletak pada denominatornya: PDB Indonesia yang sangat besar. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah pertanda positif yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pertambangan dan memiliki pilar-pilar lain yang kuat. Namun, di sisi lain, ini juga menyiratkan bahwa potensi kontribusi fiskal dan ekonomi dari sektor pertambangan yang begitu besar mungkin belum sepenuhnya dioptimalkan untuk pembangunan nasional. Peringkat ke-3 dalam nilai produksi absolut tetapi peringkat ke-18 dalam kontribusi relatif menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penarikan pajak dan royalti, dampak pengganda (multiplier effect) ke sektor lain, dan sejauh mana kekayaan mineral tersebut benar-benar ditranslasikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sepadan dengan skala dan dampak negatif ekstraksinya.
Sekali lagi, laporan MCI 2025 jelas adalah dokumen yang lebih daripada sekadar tabel nilai dan peringkat. Ia adalah sebuah dokumen politik ekonomi yang kaya, yang menyoroti perjuangan negara-negara kaya sumberdaya untuk mengubah anugerah geologis menjadi berkah pembangunan yang seharusnya berkelanjutan. Pelajaran-pelajaran yang diungkap—ketergantungan yang dalam, diskoneksi dengan SDGs, volatilitas metodologis, divergensi antara nilai dan kontribusi, serta pentingnya analisis dinamis—berfungsi sebagai panduan penting bagi para pembuat kebijakan bila memang bersungguh-sungguh menginginkan keberlanjutan itu.
Bagi kita di Indonesia, laporan ini adalah sebuah cermin yang merefleksikan keberhasilan dalam ambisi meningkatkan skala produksi dan kontribusi ekonomi pertambangan, namun sekaligus memeringatkan kita atas risiko ketergantungan yang meningkat dan tantangan untuk memastikan bahwa kekayaan luar biasa yang digali dari perut Bumi benar-benar melayani cita-cita pembangunan bangsa secara keseluruhan. Risiko dan tantangan itu sedang meningkat, dan karenanya kita semua perlu mengelola sektor pertambangan dengan kehati-hatian ekstra.
*Provokator Keberlanjutan, penulis buku “Mengurai Benang Kusut Indonesia: Jokowonomics di Bawah Cengkeram Korporasi” (2020). (Foto: Dok issf.or.id)